SEMANTIK
Makna
bahasa juga merupakan satu tataran linguistik. Semantik, dengan objeknya yakni
makna, berada di seluruh atau di semua tataran yang bangun membangun ini: makna
berada di dalam tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. oleh karena itu,
penamaan tataran untuk semantik agak kurang tepat, sebab dia bukan satu tataran
dalam arti unsur pembangun satuan lain yang lebih besar, melainkan merupakan
unsur yang berada pada semua tataran itu, meskipun sifat kehadirannya pada tiap
tataran itu tidak sama.
Hockett
(1954) misalnya, salah seorang tokoh strukturalis menyatakan bahwa bahasa
adalah suatu sistem yang kompleks dari kebiasaan-kebiasaan. Sistem bahasa ini
terdiri dari lima subsistem, yaitu subsistem gramatika, subsistem fonologi,
subsistem morfofonemik, subsistem semantik, dan subsistem fonetik. Subsistem
gramatika, fonologi, dan morfofonemik bersifat sentral. Sedangkan subsistem
semantik dan fonemik bersifat periferal. Objek semantik adalah sangat tidak
jelas, tak dapat diamati secara empiris, sebagaimana subsistem gramatika
(morfologi dan sintaksis). semantik adalah tiak ada artinya, sebab kedua
komponen itu, signifian dan signifie, merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan.
1. HAKIKAT
MAKNA
Menurut
de Saussure setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari dua
komponen, yaitu komponen signifian atau “yang mengartikan” yang wujudnya berupa
runtunan bunyi, dan komponen signifie atau “yang diartikan” yang wujudnya
berupa pengertian atau konsep (yang dimiliki oleh signifian).
2. JENIS MAKNA
Karena bahasa
itu digunakan untuk berbagai kegiatan dan keperluan dalam kehidupan
bermasyarakat, maka makna bahasa itu pun menjadi bermacam-macam bila dilihat
dari segi atau pandangan yang berbeda.
2.1. Makna
Leksikal, Gramatikal, dan Kontekstual
Makna
leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks
apa pun. Misalnya, leksem kuda memiliki makna leksikal ‘sejenis binatang
berkaki empat yang bisa dikendarai’. Dengan contoh itu dapat juga dikatakan
bahwa makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan
hasil observasi indra kita, atau makna apa adanya.
Berbeda
dengan makna leksikal, makna gramatikal baru ada kalau terjadi proses
gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi.
Umpamanya, dalam proses afiksasi prefiks ber dengan dasar baju melahirkan makna
gramatikan ‘mengenakan atau memakai baju’.
Makna
kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu
konteks.
2.2. Makna
Referensial dan Non Referensial
Sebuah
kata atau leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensnya, atau
acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata
yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Sebaliknya
kata-kata seperti dan, atau, dan karena adalah termasuk kata-kata yang tidak
bermakna ferensial, karena kata-kata itu tidak mempunyai referens.
2.3. Makna
Denotatif dan Makna Konotatif
Makna
denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki
oleh sebuah leksem. Umpamanya, kata babi bermakna denotatif ‘sejenis binatang
yang biasa diternakkan untuk dimanfaatkan dagingnya’.
Makna
konotatif adalah makna lain yang “ditambahkan” pada makna denotatif tadi yang
berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan
kata tersebut.
2.4. Makna
Konseptual dan Makna Asosiatif
Makna
konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks
atau asosiasi apa pun. Kata kuda memiliki makna konseptual ‘sejenis binatang
berkaki empat yang biasa dikendarai’.
Makna
asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan
adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya,
kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian.
Makna
konotatif termasuk dalam makna asosiatif adalah karena kata-kata tersebut
berasosiasi dengan nilai rasa terhadap kata itu. Kata babi, misalnya,
berasosiasi dengan rasa jijik, haram, dan kotor (bagi yang beragama Islam).
2.5. Makna Kata
dan Makna Istilah
Pada
awalnya yang dimiliki sebuah kata adalah makna leksikal, makna denotatif atau
makna konseptual. Namun, dalam penggunaannya makna kata itu baru menjadi jelas
kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks
situasinya.
Yang
disebut dengan istilah mempunyai makna yang pasti, yang jelas, yang tidak
meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat. oleh karena itu, sering dikatakan
bahwa istilah itu bebas konteks. Hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya
digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu.
2.6. Makna
Idiom dan Peribahasa
Idiom
adalah satu ujaran yang maknanya tidak dapat “diramalkan” dari makna
unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Umpamanya,
secara gramatikal bentuk menjual rumah bermakna ‘yang menjual menerima uang dan
yang membeli menerima rumahnya’.
Dua
macam idiom, yaitu yang disebut idiom penuh dan idiom sebagian. Yang dimaksud
dengan idiom penuh adalah idiom yang semua unsur-unsurnya sudah melebuh menjadi
satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu.
Bentuk-bentuk seperti membanting tulang, menjual gigi, dan meja hijau termasuk
contoh idiom penuh. Idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih
memiliki makna leksikalnya sendiri. misalnya buku putih yang bermakna ‘buku
yang memuat keterangan resmi mengenai suatu kasus’.
Yang
disebut peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari
makna unsur-unsurnya karena adanya “asosiasi” antara makna asli dengan maknanya
sebagai peribahasa. Umpamanya, peribahasa ‘seperti anjing dengan kucing’ yang
bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur.
3. RELASI MAKNA
Relasi
makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu
dengan satuan bahasa lainnya. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini
biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisemi,
homonimi, hiponimi, ambiquiti, dan redundansi.
3.1. Sinonim
Sinonim
atau sinonimi adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna
antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Misalnya, antara kata
betul dengan kata benar.
Dua
buah ujaran yang bersinonim maknanya tidak akan persis sama. Ketidaksamaan itu
terjadi karena berbagai faktor, antara lain:
- Pertama, faktor
waktu. Umpamanya kata hulubalang bersinonim dengan kata komandan.
- Kedua, faktor
tempat atau wilayah. Misalnya, kata saya dan beta adalah dua buah kata yang
bersinonim.
- Ketiga,
faktor keformalan. Misalnya, kata uang dan duit adalah dua buah kata yang
bersinonim.
- Keempat,
faktor sosial. Umpamanya, kata saya dan aku adalah dua buah kata yang
bersinonim.
- Kelima,
bidang kegiatan. Umpamanya kata matahari dan surya adalah dua buah kata yang
bersinonim.
- Keenam,
faktor nuansa makna. Umpamanya kata-kata melihat, melirik, menonton, meninjau,
dan mengintip adalah sejumlah kata yang bersinonim.
Dari
keenam faktor yang dibicarakan di atas, bisa disimpulkan bahwa dua buah kata
yang bersinonim tidak akan selalu dapat dipertukarkan atau disubstitusikan.
3.2. Antonim
Antonim
atau antonimi adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang
maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu
dengan yang lain. Misalnya, kata buruk berantonim dengan kata baik.
Dilihat
dari sifat hubungannya, maka antonimi itu dapat dibedakan atas beberapa jenis,
antara lain:
- Pertama,
antonimi yang bersifat mutlak. Umpamanya kata hidup berantonim secara mutlak
dengan kata mati.
- Kedua,
antonimi yang bersifat relatif atau bergradasi. Umpamanya kata besar dan kecil
berantonimi secara relatif.
- Ketiga,
antonimi yang bersifat relasional. Umpamanya antara kata membeli dan menjual,
antara kata suami dan istri, dan antara kata guru dan murid. Antonimi jenis ini
disebut relasional karena munculnya yang satu harus disertai dengan yang lain.
- Keempat,
antonimi yang bersifat hierarkial. Umpamanya kata tamtama dan bintara
berantonim secara hierarkial; juga antara kata gam dan kilogram.
3.3. Polisemi
Sebuah
kata atau satuan ujaran disebut polisemi kalau kata itu mempunyai makna lebih
dari satu. Umpamanya, kata kepala yang setidaknya mempunyai makna bagian tubuh
manusia.
Dalam
kasus polisemi ini, biasanya makna pertama (yang didaftarkan di dalam kamus) adalah
makna sebenarnya, makna leksikalnya, makna denotatifnya, atau makna
konseptualnya.
3.4. Homonimi
Homonimi
adalah dua buah kata atau satu ujaran yang bentuknya “kebetulan” sama; maknanya
tentu saja berbeda, karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang
berlainan. Umpamanya, antara kata pacar yang bermakna “inai” dan kata pacar
yang bermakna “kekasih”.
Pada
kasus homonimi ini ada dua istilah lain yang biasa dibicarakan, yaitu homofoni
dan homografi. Yang dimaksud dengan homofoni adalah kesamaan bunyi (fon) antara
dua satuan ujaran tanpa memperhatian ejaannya, apakah ejaannya sama ataukah
berbeda.
Istilah
homografi mengacu pada bentuk ujaran yang sama ortografinya atau ejaannya,
tetapi ucapan dan maknanya tidak sama. Dalam bahasa Indonesia bentuk-bentuk
homografi hanya terjadi karena ortografi untuk fonem /e/ dan fonem /ә/ sama
lambangnya yaitu huruf <e>.
Patokan pertama
yang harus dipegang adalah bahwa homonimi adalah dua buah bentuk ujaran atau
lebih yang “kebetulan” bentuknya sama, dan maknanya tentu saja berbeda.
Sedangkan polisemi adalah sebuah bentuk ujaran yang memiliki makna lebih dari
satu.
3.5. Hiponimi
Hiponimi
adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup
dalam makna bentuk ujaran yang lain. Umpamanya antara kata merpati dan kata
burung. Di sini kita lihat makna kata merpati tercakup dalam makna kata burung.
Merpati adalah burung; tetapi burung bukan hanya merpati.
3.6. Ambiquiti
atau Ketaksaan
Ambiquiti
atau ketaksaan adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran
gramatikal yang berbeda. Tafsiran gramatikal yang berbeda ini umumnya terjadi
pada bahasa tulis, karena dalam bahasa tulis unsur suprasegmental tidak dapat
digambarkan dengan akurat. Misalnya, bentuk buku sejarah baru dapat ditafsirkan
maknanya menjadi (1) buku sejarah itu baru terbit, atau (2) buku itu memuat
sejarah zaman baru.
Ketaksaan
dalam bahasa lisan biasanya adalah karena ketidakcermatan dalam menyusun
konstruksi beranaforis. Yang perlu diingat adalah konsep bahwa homonimi adalah
dua buah bentuk atau lebih yang kebetulan bentuknya sama, sedangkan, ambiquiti
adalah sebuah bentuk dengan dua tafsiran makna atau lebih.
3.7. Redundansi
Istilah
redundansi biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihannya penggunaan unsur
segmental dalam suatu bentuk ujaran. Umpamanya kalimat bola itu ditendang oleh
Dika tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan bola itu ditendang Dika.
4. PERUBAHAN
MAKNA
Secara
sinkronis makna sebuah kata atau leksem tidak akan berubah; tetapi secara
diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Maksudnya, dalam masa yang relatif
singkat, makna sebuah kata akan tetap sama, tidak berubah; tetapi dalam waktu
yang relatif lama ada kemungkinan makna sebuah kata akan berubah.
Faktor
penyebab perubahan makna
- Pertama, perkembangan
dalam bidang ilmu dan teknologi
- Kedua,
perkembangan sosial budaya
- Ketiga,
perkembangan pemakaian kata. Setiap bidang kegiatan keilmuan biasanya mempunyai
sejumlah kosakata yang berkenaan dengan bidangnya itu.
- Keempat,
pertukaran tanggapan indra. Misalnya, rasa getir, panas, dan asin ditangkap
dengan alat indra perasa, yaitu lidah.
- Kelima,
adanya asosiasi. Yang dimaksud dengan adanya asosiasi di sini adalah adanya
hubungan antara sebuah bentuk ujaran dengan sesuatu yang lain yang berkenaan
dengan bentuk ujaran itu, sehingga dengan demikian bila disebut ujaran itu maka
yang dimaksud adalah sesuatu yang lain yang berkenaan dengan ujaran itu.
Perubahan
makna kata atau satuan ujaran itu ada beberapa macam. Ada perubahan yang
meluas, ada yang menyempit, ada juga yang berubah total. Perubahan yang meluas,
artinya kalau tadinya sebuah kata bermakna “A”, maka kemudian menjadi bermakna
“B”.
Perubahan
makna yang menyempit, artinya kalau tadinya sebuah kata atau satuan ujaran itu
memiliki makna yang sangat umum tetapi kini maknanya menjadi khusus atau sangat
khusus.
Perubahan makna
secara total, artinya makna yang dimiliki sekarang sudah jauh berbeda dengan
makna aslinya. Umpamanya, kata ceramah dulu bermakna ‘cerewet, banyak cakap’,
sekarang bermakna ‘uraian mengenai suatu hal di muka orang banyak’.
5. MEDAN MAKNA
DAN KOMPONEN MAKNA
Kata-kata
atau leksem-leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan atas
kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki
kata-kata itu. Umpamanya, kata-kata kuning, merah, hijau, biru, dan ungu berada
dalam satu kelompok, yaitu kelompok warna.
Kata-kata
yang berada dalam satu kelompok lazim dinamai kata-kata yang berada dalam satu
medan makna atau satu medan leksikal.
5.1. Medan
Makna
Yang
dimaksud dengan medan makna (semantic domain, semantic field) atau medan
leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan
karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam
semesta tertentu. Misalnya, nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga.
Kata-kata
atau leksem-leksem yang mengelompokkan dalam satu medan makna, bedasarkan sifat
hubungan semantisnya dapat dibedakan atas kelompok medan kolokasi dan medan
set. Kolokasi menunjuk pada hubungan sintagmantik yang terdapat antara
kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu.
Kelompok
set menunjuk pada hubungan paradigmatik, karena kata-kata yang berada dalam
satu kelompok set itu saling bisa disubstitusikan. Sekelompok kata yang
merupakan satu set biasnya mempunyai kelas yang sama, dan tampaknya juga
merupakan satu kesatuan. Umpamanya, kata remaja merupakan tahap perkembangan
dari kanak-kanak menjadi dewasa. Pengelompokan kata atas kolokasi dan set ini
besar artinya bagi kita dalam memahami konsep-konsep budaya yang ada dalam
suatu masyarakat bahasa.
5.2. Komponen
Makna
Makna
yang dimiliki oleh setiap kata itu terdiri dari sejumlah komponen (yang disebut
komponen makna), yang membentuk keseluruhan makna kata itu. Komponen makna ini
dapat dianalisis, dibutiri, atau disebutkan satu per satu, berdasarkan
“pengertian-pengertian” yang dimilikinya. Umpamanya, kata ayah memiliki
komponen makna /+manusia/, /+dewasa/, /+jantan/, /+kawin/, dan /+punya anak.
Analisis
komponen makna ini dapat dimanfaatkan untuk mencari perbedaan dari
bentuk-bentuk yang bersinonim. Kegunaan analisis komponen yang lain ialah untuk
membuat prediksi makna-makna gramatikal afiksasi, reduplikasi, dan komposisi
dalam bahasa Indonesia.
Kemudian,
oleh Chomsky (1965) prinsip-prinsip analisis yang dilakukan Roman Jacobson dan
para ahli antropologi itu digunakan untuk memberi ciri-ciri gramatikal dan
ciri-ciri semantik terhadap semua morfem dalam daftar morfem yang melengkapi
tata bahasa generatif transformasinya.
5.3. Kesesuaian
Semantis dan Sintaktis
pada
5.2. telah disebutkan bahwa berterima tidaknya sebuah kalimat bukan hanya
masalah gramatikal, tetapi juga masalah semantik.
Contoh:
Ÿ
Kambing yang Pak Udin terlepas lagi
Ÿ
Segelas kambing minum setumpuk air
Ÿ
Kambing itu membaca komik
Ÿ
Penduduk DKI Jakarta sekarang ada 50 juta orang
Ketidakberterimaan
kalimat Kambing yang Pak Udin terlepas lagi adalah karena kesalahan gramatikal,
yaitu adanya konjungsi yang antara kambing dan Pak Udin.
Kalimat
Segelas kambing minum setumpuk air tidak berterima bukan karena kesalahan
gamatikal tetapi karena kesalahan persesuaian leksikal.
Ketidakberterimaan
kalimat Kambing itu membaca komik adalah karena tidak ada persesuaian antara
kata kambing sebagai pelaku dengan kata membaca sebagai perbuatan yang
dilakukan kambing itu.
Mari
kita melihat kembali kalimat ‘segelas kambing minum setumpuk air’ dan kalimat
‘kambing itu membaca komik’. Kedua kalimat itu tidak berterima, bukanlah karena
kesalahan gramatikal maupun informasi, melainkan karena kesalahan semantik.
Kesalahan itu berupa tidak adanya persesuaian semantik di antara
konstituen-konstituen yang membangun kalimat itu.
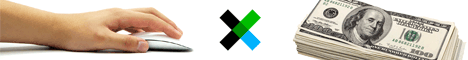
No comments:
Post a Comment