Candi Cangkuang adalah sebuah candi Hindu yang terdapat di Kampung Pulo,
wilayah Cangkuang, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Candi ini juga yang
pertama kali ditemukan di Tatar Sunda serta merupakan satu-satunya candi Hindu
di Tatar Sunda.
Nama Candi Cangkuang disesuaikan dengan nama desa dimana candi itu
ditemukan. Desa Cangkuang berasal dari nama pohon yang banyak terdapat
disekitar makam Embah Dalem Arif Muhammad, namanya pohon Cangkuang, pohon ini
sejenis pohon pandan dalam bahasa latinnya ( Pandanus Furcatus ), tempo dulu
daunnya dimanfaatkan untuk membuat tudung, tikar atau pembungkus gula aren.
Embah Dalem Arif Muhammad dan kawan-kawan beserta masyarakat setempatlah yang
membendung daerah ini, sehingga terjadi sebuah danau dengan nama "Situ
Cangkuang" kurang lebih abad XVII.
Embah Dalem Arif Muhammad dan kawan-kawan berasal dari kerajaan Mataram
di Jawa Timur. Mereka datang untuk menyerang tentara VOC di Batavia sambil
menyebarkan Agama Islam di Desa Cangkuang Kabupaten Garut. Waktu itu di Kampung
Pulo salah satu bagian wilayah dari desa Cangkuang sudah dihuni oleh penduduk
yang beragama Hindu. Namun secara perlahan namun pasti, Embah Dalem Arif
Muhammad mengajak masyarakat setempat untuk memeluk Agama Islam.
Desa Cangkuang terletak disebelah utara kabupaten Garut masuk Kecamatan
Leles, tepatnya berjarak 17 km dari
Garut atau 46 km dari Bandung .
Untuk menuju situs Cangkuang dari arah Bandung ,
bisa menggunakan mobil pribadi atau umum. Dari arah Bandung menuju Garut kita akan ketemu dengan
kecamatan Leles, ketika sampai di Leles ada sebuah papan petunjuk yang sangat
jelas yang menunjukkan posisi Candi Cangkuang. Masuk ke dalam sejauh kurang
lebih 3 km, dengan jalan beraspal dapat dilalui oleh kendaraan baik roda dua
maupun empat, bahkan masih dipertahankan angkutan tradisional delman ( andong
). Apabila ditempuh dengan jalan kaki memerlukan waktu kurang lebih 30 menit.
Udara didaerah ini tergolong sejuk, karena terletak di ketinggian 700 m diatas
permukaan air laut. Disepanjang perjalanan dari Leles ke desa Cangkuang kita
akan menyaksikan indahnya sawah yang hijau, disebelah utara kita akan melihat
Gunung Haruman, dan disebelah barat akan nampak Gunung Mandalawangi dan Gunung
Guntur yang menjulang tinggi.
Gerbang yang tidak terlalu besar akan menyambut kehadiran para
pengunjung, bahkan lokasi parkir bagi para pengunjung hanya muat untuk 3 mobil
ukuran kecil sejenis sedan dan minibus. Untuk bus besar bisa diparkir ditepi
jalan desa. Sejenak kita bisa beristirahat ditepi situ, sambil menikmati
makanan kecil yang sudah kita bawa. Teduh rasanya memandangi air situ yang
bening kehijauan dan udara yang sejuk. Untuk mencapai Candi Cangkuang kita
harus menyeberangi situ, kurang lebih berjarak 500 meter dari tempat gerbang
masuk. Rakit dari bambu siap mengantarkan kita dengan ongkos 3000 perorang,
dimana satu rakit kapasitas maksimalnya 25 orang. Kurang lebih setelah 10 menit
berada diatas rakit, sampailah kita dilokasi Candi Cangkuang. Pagi hari rasanya
lebih indah ketika kita mengunjungi candi tersebut, karena selain candi
tersebut terletak ditanah yang paling tinggi diantara bangunan-bangunan lain
ditempat itu, kabut pagi yang menyembul diantara pohon-pohon besar di sekitar
candi menambah kesan angker candi, namun hal itu justru menambah pesona tersendiri
dari Candi Cangkuang.
Candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1966 oleh tim peneliti
Harsoyo dan Uka Candrasasmita berdasarkan laporan Vorderman (terbit tahun 1893)
mengenai adanya sebuah arca yang rusak serta makam leluhur Arif Muhammad di Leles.
Selain menemukan reruntuhan candi, terdapat pula serpihan pisau serta batu-batu
besar yang diperkirakan merupakan peninggalan jaman megalitikum. Penelitian
selanjutnya (tahun 1967 dan 1968) berhasil menggali bangunan makam.
Walaupun hampir bisa dipastikan bahwa candi ini merupakan peninggalan
agama Hindu (kira-kira abad ke-8 M, satu jaman dengan candi-candi di situs
Batujaya dan Cibuaya?), yang mengherankan adalah adanya pemakaman Islam di
sampingnya.
Candi Cangkuang terdapat di sebuah pulau kecil yang bentuknya memanjang
dari barat ke timur dengan luas 16,5 ha. Pulau kecil ini terdapat di tengah
danau Cangkuang pada koordinat 106°54'36,79" Bujur Timur dan 7°06'09"
Lintang Selatan. Selain pulau yang memiliki candi, di danau ini terdapat pula
dua pulau lainnya dengan ukuran yang lebih kecil.
Bangunan Candi Cangkuang yang sekarang dapat kita saksikan merupakan
hasil pemugaran yang diresmikan pada tahun 1978. Candi ini berdiri pada sebuah
lahan persegi empat yang berukuran 4,7 x 4,7 m dengan tinggi 30 cm. Kaki
bangunan yang menyokong pelipit padma, pelipit kumuda, dan pelipit pasagi
ukurannya 4,5 x 4,5 m dengan tinggi 1,37 m. Di sisi timur terdapat penampil
tempat tangga naik yang panjangnya 1,5 m dan lébar 1,26 m.
Tubuh bangunan candi bentuknya persegi empat 4,22 x 4,22 m dengan tinggi
2,49 m. Di sisi utara terdapat pintu masuk yang berukuran 1,56 m (tinggi) x 0,6
m (lebar). Puncak candi ada dua tingkat: persegi empat berukuran 3,8 x 3,8 m
dengan tinggi 1,56 m dan 2,74 x 2,74 m yang tingginya 1,1 m. Di dalamnya
terdapat ruangan berukuran 2,18 x 2,24 m yang tingginya 2,55 m. Di dasarnya
terdapat cekungan berukuran 0,4 x 0,4 m yang dalamnya 7 m (dibangun ketika
pemugaran supaya bangunan menjadi stabil).
Di antara sisa-sisa bangunan candi, ditemukan juga arca (tahun 1800-an)
dengan posisi sedang bersila di atas padmasana ganda. Kaki kiri menyilang datar
yang alasnya menghadap ke sebelah dalam paha kanan. Kaki kanan menghadap ke
bawah beralaskan lapik. Di depan kaki kiri terdapat kepala sapi (nandi) yang
telinganya mengarah ke depan. Dengan adanya kepala nandi ini, para ahli
menganggap bahwa ini adalah arca Siwa. Kedua tangannya menengadah di atas paha.
Pada tubuhnya terdapat penghias perut, penghias dada dan penghias telinga.
Keadaan arca ini sudah rusak, wajahnya datar, bagian tangan hingga kedua
pergelangannya telah hilang. Lebar wajah 8 cm, lebar pundak 18 cm, lebar
pinggang 9 cm, padmasana 38 cm (tingginya 14 cm), lapik 37 cm & 45 cm
(tinggi 6 cm dan 19 cm), tinggi 41 cm.
Candi Cangkuang sebagaimana terlihat sekarang ini, sesungguhnya adalah
hasil rekayasa rekonstruksi, sebab bangunan aslinya hanyalah 35%-an. Oleh sebab
itu, bentuk bangunan Candi Cangkuang yang sebenarnya belumlah diketahui.
Candi ini berjarak sekitar 3 m di sebelah selatan makam Arif Muhammad.
Lebih unik lagi disamping Candi cangkuang terdapat sebuah pemukiman yang
dinamakan dengan Kampung Pulo. Sebuah kampung kecil yang terdiri dari enam buah
rumah dan enam kepala keluarga, tidak boleh menambah atu mengurangi jumlah
bangunan, serta rumahnya harus saling berhadapan. Disana tidak diperbolehkan
menggunakan Gong dari perunggu Ketentuan ini harus ditepati, dan sudah
merupakan ketentuan adat kalau jumlah rumah dan kepala keluarga itu harus enam.
Apabila keturunan Eyang Arif Muhammad menikah maka anaknya harus ada yang
keluar dari kampung tersebut. Dan hak waris jatuh kepada anak perempuan.
Oleh karena itu bagi Kampung Pulo Desa Cangkuang sukar atau relatif lama
untuk berkembang, baik rumahnya atau penduduknya dari keenam kepala keluarga
tersebut. Mata pencaharian masyarakat disana ada yang bertani dan menangkap
ikan, tetapi setelah dibuka menjadi objek wisata masyarakatnya ada yang menjadi
pegawai negeri (PNS) dan ada pula yang berdagang. Penduduk yang menempati
kampung ini merupakan penduduk keturunan ke tujuh dari Eyang Dalem Arif
Muhammad. Karena uniknya tempat ini, baik dari sejarah maupun lokasinya,
membuat daya tarik tersendiri buat wisatawan baik domestik maupun luar negeri
untuk mengunjungi tempat ini. Menurut petugas, "tiap hari selalu ada wisatawan
asing yang berkunjung kesisni, belum lagi diakhir minggu biasanya banyak
dikunjungi oleh anak-anak sekolah untuk memperdalam pengetahuan sejarah. Namun
begitu, faktor kebersihan dan keindahan nampaknya kurang mendapat perhatian
serius dari Dinas Pariwisata yang mengelola tempat ini. Selain itu fasilitas
MCK juga kurang memadai, sehingga ke depan agar tempat ini tetap menarik buat
para wisatawan, pihak-pihak terkait harus memperbaiki dan melengkapi
fasilitas-fasilitas yang ada.
Eyang Arif, begitu keturunan Arif Muhammad memanggil moyangnya,
mengajarkan bahwa umat beragama Hindu tidak bekerja pada hari Rabu. Mereka
lebih banyak memperdalam agama yang dianutnya. Oleh sebab itu, adat tersebut
diambil dan disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan keturunannya hingga
saat ini.
Di kampung Pulo tidak ada tingkatan atau lapisan untuk membedakan warga
satu dengan yang lainnya dan yang ada hanya kuncen sebagai pemandu dalam
berziarah dan sebagai penengah dalam bermusyawarah.
Kebiasaan lain adalah melakukan ritual keagamaan dengan menggunakan
sesaji dan dupa saat berdoa di makam. Sama halnya dengan kebiasaan dalam agama
Hindu yang menggunakan dupa dan sesaji saat berdoa, masyarakat adat di tempat
ini juga melakukan hal yang sama. Jadi agama Islam disana masih terkontaminasi
oleh adat kebiasaan Hindu.
.
Seluruh kebiasaan yang ditinggalkan oleh Eyang Arif tersebut tetap hidup
hingga saat ini. Meskipun banyak dari keturunannya yang tidak lagi tinggal di
Kampung Pulo, mereka tetap melaksanakan adat sesuai dengan apa yang telah
diajarkan.
Referensi
Hasil observasi
di Candi Cangkuang pada tanggal 05 April 2009.
http://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Cangkuang.
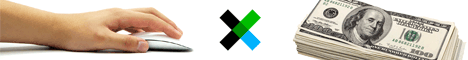
No comments:
Post a Comment